Surat Keenam
Filosofi Garam : Sebuah Etika Memandang Pribadi
Aku selalu mengatakan bahwa garam adalah bagian dari hidup siapapun. Rasanya sangat asin seolah tak berharga. Namun itulah kita, setiap detik kita, kita bergantung dengan lainnya. Aku melambangkan garam dengan hidup kita. Setiap masakan tak mampu memberi ruh ketika garam kehilangan tahtanya. Setiap garam merupakan etika kita memandang pribadi orang-orang yang kita sayangi sebagai suatu hal yang sangat menakjubkan. Dengan segenap hati dan jiwa. Tanpa hiperbola atau eufemisme.
Aku pernah membayangkan ketika garam pindah ke Pluto. Bagaimana aku mampu menjalani hidup ketika tanpamu. Bagaimana aku mampu menulis jika tanpamu. Bagaimana aku mampu melakukan apapun jika tanpamu. Tanpa tatapanmu, ataupun belaianmu di rambut pirangku.
Begitulah garam. Setiap masakan akan hampa, jika garam menghilang. Begitulah garam. Setiap deburan ombak akan terasa hampa jika lautnya tak berasa kelat asin. Atau begitulah garam dalam tubuh kita, akan terasa aneh jika keringat kita berasa strawberry. Begitulah kita, bergantung satu sama lain. Siapapun itu, dimanapun itu. Ini bukan berlebihan, tapi aku menanggap ini semua terjadi karena diciptakan bersama.
Aku masih ingat, ketika ruhku terbaring lunglai disamping manusia hebat. Lalu dia mencoba menjejaliku dengan putingnya agar aku mampu meneruskan hidup. Itu juga terasa sangat asin sekali. Tak ada pilihan. Karena begitulah manusia sosial. Tak ada pilihan untuk tidak bergantung. Karena dia segerbong rangkaian kereta api yang tak mungkin hidup sendiri. Dia akan kehilangan ruh dan namanya sebagai kereta api jika dia hanya sendiri. Mungkin saja dia tak akan bisa berjalan. Dan kehilangan jati dirinya sebagai kereta api. Hingga tak akan ada lagi bunyi tut tut tut tut, puuumm, ketika dia tertawa. Dan tak ada pilihan yang lebih bijak jika kita kehilangan serangkaian sistem dalam kehidupan kita.
Cenderung begitu. Karena begitulah adanya.
---
Dentuman saxophone terdengar ketika surat ini ada. Dentumannya terasa sejuk dan menyentuh segenap organ tubuh kita. Melayang dan merasuk ke dalamnya. Seperti aku pernah jatuh cinta kepada Vanesa Mae dalam I’m doun for a jhonhy, dan membuat sepasang tulisan diatas ciuman indah perut mungilku.
Dentuman saxophone dan setiap aliran ruh yang keluar kadang tidak memekakkan telingaku yang lahir dari instrumen alam ini. Antara dangdut, jazz, rock, pop, seriosa tak ada yang berbeda. Cenderung kualifikasi musik ditenggarai sebagai suatu sistem tak bertuan. Semua boleh memaknai dengan cinta. Tapi kadangkala kita memaknai dengan tidak ril. Dangdut dimaknai sebagai instrument sepihak. Kampungan, norak, kelas bawah, jorok, menjadi satu dan padu dalam setiap gambarannya. Hingga sinisme muncul dan tingkatan prestise juga hadir melengkapinya. Memang tak ada yang tak berkelas. Strata menjadi acuan, disadari atau tidak. Atasan bawahan, majikan budak, hitam putih hingga musik yang mewarnai juga menjadi quality control kepribadian. Atau ini berarti pembatasan secara sempit. Padahal dia sama. Setiap dentuman yang keluar adalah garam. Melengkapi dentuman-dentuman yang lain. Dia indah, dan menjadi apa adanya sesuai warnanya seperti lainnya. Tuhannya tetap satu, musik. Tapi mungkin caranya berbeda. Dentumannya berbeda. Hingga telinganya berbeda. Tak ada yang salah.
Sebutannya mahluk sosial. Tapi penyampaiannya berbeda dan istilahnya berbeda. Garam, mungkin itu tentang aku. Dan harapanku. Sama saja seperti lainnya. Mungkin dengan lebih vulgar begini semua akan tau. Bahwa kehadirannya, bukan hanya pelengkap. Tapi memang dia harus hadir. Dangdut harus begitu juga.
Ini awal merasai dari hati memandang pribadi.
---
Ini jadi sangat sulit. Dan menjadi sesuatu yang sulit. Rumit. Karena keluarga adalah garam yang sesungguhnya. Mungkin saja murni, tak tercemari. Rasanya pekat. Akan berbeda dengan lainnya. Atau akan menjadi lain di lidah yang lain. Saat keluarga tak ada, kebahagiaan hanya akan menjadi semu. Atau ketika kita bersedih akan menjadi sulit. Dekapan, belaian atau hanya sekedar omelan akan menjadi kebutuhan yang berpangkat semilyar. Dan semua akan hilang.
‘itu tak mudah dilakukan, tapi begitulah kebutuhannya’
Ketika kita didalam rumah, tampat berlindung paling aman. Kita akan menjadi diri kita sendiri. Dan menganggap rumah adalah tempat dimana manusia-manusia sejati hidup. Tak ada manusia-manusia mesin yang harus mendaratkan cambukan di tubuh kita. Sehingga kita akan aman menjadi manusia sejati. Namun, kadangkala tak begitu. Karena kita juga harus menjadi manusia mesin dirumah kita sendiri. Di tempat yang paling aman. Hingga kita tersedu di tempat yang paling aman. Hanya kaki langit yang tau. Bahwa temaran berwarna jingga atau kelam yang akan tiba. Tapi temaram tak pernah berubah. Tetap tak berpindah waktu. Hanya berubah-ubah saja. Karena etika ada di dalam hati dan pikiran. Keluarga tetaplah membutukan garam. Jika dia berubah rasa, hanya etika dan perasaan yang mampu menjawab. Seandainya kita tau, bahwa itu menggunakan etika dan perasaan. Mungkin rumah akan menjadi tempat yang sangat aman sekali. Itu hanya sekecil cerita. Tentang etika, musik dan rumah. Yang aku gambarkan dengan garam.
Begitulah aku memandang pribadi.
Pluto, 18 Oktober 2010

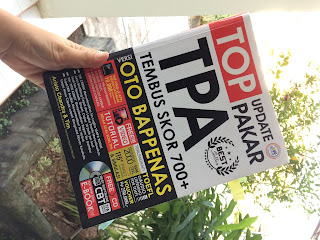


Komentar