Di Tengah Kangen
Aku sakit lagi. Ini untuk ketiga kalinya aku sakit setelah sore itu di teras hatiku.
Air mata tak tertumpahkan lewat mata lagi. Hati pun ikut larut. Aku sakit lagi. Kuulang lagi. Untuk ketiga kalinya. Ah…ini seperti klimaks. Jika tiga kali terjadi ini adalah tanda, bahwa dunia tak berpihak pada keinginanku, tapi pada hatiku.
Aku bertanya pada Tama petang itu. “Tama adakah salahku padamu?”. Tama diam saja menanggapi pertanyaanku. Aku pikir, diam adalah tanggapan Tama yang terindah. Daripada dia bicara, tapi aku tak mengerti apa maksudnya.
Petang itu, aku lewati dengan Tama. Bicara dengan mesra di tengah teras hatiku. Di temani cahaya temaran malam yang syahdu. Disekeliling kami, ada orang-orang yang kusayang memperhatikan aku yang berceloteh ria.
Aku tidak pernah bercerita seceria ini. Aku pikir, menggunakan sepatu merah lebih indah daripada sepatu putih manis yang kubeli di salah satu toko elite di Palembang kemarin. Ah, waktu nalarku telah hilang. Aku ceria namun aku memikirkan sepatu merah baru dengan riasan sederhana di atasnya. Dengan aksen tumit non highheels.
Aku ceria. Sangat. Kemanjaanku yang timbul dari beberapa kemanjaan yang dulu pernah hilang. Aku tertawa bebas, memukul bahu Tama sesekali. Atau tanganku reflex memukul dengan boneka bebek yang kugigit bibirnya sepanjang malam. Ah aku tak mendapatkan bibir bebek nanti malam. Aku sedang tidak dirumahku sendiri. Urgh…aku ingin sekali membawa bebekku kemari. Namun, sudut kesalahan kemarin menatapku erat-erat. Dan berkata, “Kau Sudah dewasa Jan, bebek ini hanya layak ditempat tidurmu. Bukan ditengah teras ini”
Uff…sungguh akan kukutuk sudut kesalahan ini. Dia yang mengaturku, melalui tatapannya. Seakan Tuhan menyetujui ulahnya kali ini, karena aku hanya mengangguk,” iya”.
***
Ah….aku hanya duduk malam ini, tanpa Tama. Tama tak bercengkrama lagi denganku. Dia entah kemana, tak mengabariku lagi. Segala cara kulakukan untuk menghubunginya. Tapi Tama tak terlacak. Aku selalu diam. “Tama, kemarilah, sudut hati ini tak mampu diam, kau kemana gerangan??”. Aku menembangkan lagu keroncong, lagu yang sering dinyanyikan Waljinah dalam stasiun TVRI, namun aku lupa judul lagunya. Kulakukam sepanjang hari sambil menanti Tama.
“Nyanyi apa Janis?” Bunda menggentikan lagu kacauku.
***
Tama tak datang juga. Setiap lalu lalang sahabatku aku selalu menanyakan Tama. Tapi tak ada yang satupun mengetahui Tama berada dimana. Aku kelelahan. Zuhur tiba, dan Tama juga belum muncul. Lalu Zuhur ini, aku coba mengadahkan tanganku, Tuhan, jika ini ulahku atas ketakdatangannya padaku, hukumlah aku lagi. Aku mengingat Tama berulang-ulang, seperti aku menghapal pelajaran sejarah mengenai tragedy terjadinya 30 S PKI. Pratama Adityo Putro. Ada huruf Y pengganti huruf I dalam ejaan Aditya. Tak pernah kulupa, Tama memarahiku karena mengganti ejaan Y menjadi I. Ah, aku terdiam saat kau memarahiku, bukan karena kesalahanku ataupun ketakutanku salah di depanmu, tapi mengapa kau begitu menghargai nama pemberian ayah ibu mu. Padahal itu tidak pernah salah.
Aku begitu tak menghargai ayah ibuku dengan namaku.
Ah, aku memang selalu kalah denganmu, Tama.
***
Mataku kali ini mengisyaratkan lain. Aku punya ide untuk menghubungi melalui ponsel bututku ini. Kali ini kau kalah Tama, aku masih menggunakan ponsel pemberian bunda, hadiah kelulusan SMA-ku, tiga tahun yang lalu. Sedangkan kau, kau telah mengganti beberapa kali ponselmu. Padahal ponsel terakhir yang kau miliki adalah ponsel bersejarah kita. Ponsel yang selalu kita gunakan untuk menangkap moment-moment bahagia saat kita liburan di Kuta Bali waktu itu.
Kuta Bali.. sungguh indah Tama. Tak pernah bisa kulukiskan lagi, betapa aku tak berfikir menggunakan otakku lagi saat kita menantang bahaya waktu itu. Kau menculikku tengah malam (sebenarnya, aku yang minta diculik), lalu kita belajar mobil dijalanan. Hingga kita dikejar-kejar polisi karena menabrak tiang lampu merah di persimpangan empat jalan menuju hotel waktu itu. Haha… aku tertawa keras-keras waktu dibawa ke kantor polisi. Kau begitu ketakutan waktu itu, karena membuat bunda marah besar waktu itu.
“Bayangkan ma, lampu merah yang kita tabrak. Bule-bule gila itu juga ikut teriak waktu kita menabraknya, aku exicting banget”
Kau senyum saja. Lalu memelukku erat sekali. Aku bingung sekali waktu itu.
“aku takut kau kenapa-kenapa an, berjanjilah, kau menuruti kata Bunda”
(An, singkatan kata manja yang kau sebutkan padaku)
Aku tak mengindahkan kata-katamu. Aku malah mengajakmu berlari-lagi di pinggir pantai. Dan mencoba menceburkanmu di ombak yang menyapa kita malam itu. Waktu itu, setengah tiga pagi. Dan bunda tidak menangis lagi melihat ulahku kali ini.
Ketikan setiap kataku dalam sms untuk Tama malam itu, mengisyaratkan cerita kita di Kuta waktu itu. Begini bunyinya.
“Tama, Aku bingung. Kali ketiga ini Aku harus bilang apa padamu. Aku hanya kangen kamu. Kenapa tak kau susun lagi buku-buku di kamarku seperti kemarin. Aku tak berada di kamarku lagi Tama. Aku kangen melihatmu menyusun buku-bukuku di kamarku.”
Kukirim. Report : Messege sent.
***
“Janis, kau lewatkan Subuhmu lagi?”
“Ah”, aku mengerang. Aku tak mau membuka mataku lagi pagi ini. Kicau burung tak lagi mau meneriakkan kicaunya di atas genteng kamarku, dan kamar ini.
Kututup mataku lagi. Hingga Dhuha menjelang.
Bunda seperti biasa, menggeleng-geleng kepalanya, setelah teriak menangis.
***
Aku terbangun pagi sekali, subuh. Atau mungkin ini masih jam 3 pagi. Kulonggok ponselku. Tak ada balasan smsmu. Tak ada panggilan sadismu Tama. Aku tak menyukai pagi lagi Tama. Aku tak mau lagi mondar-mandir di depan teras kamarku lagi. Memarahi burung-burung yang mengajakku bicara. Oh Tuhan… Aku menyukai pagi ini sebenarnya. Aku ingin pagi ini lagi hadir. Bersama Tama. Menyeduh teh hangat dan menguyah coklat lumat-lumat.
Tama, kubuang setiap pagiku. Karena aku juga kehilanganmu
Tama, kubakar setiap kicauan burung diatas teras kamarku. Aku tak bisa melihat lagi Tama.
Tama, kuhabiskan tetesan embun pagi ini. Hingga tak berair lagi.
Kau, mencegah aku merindukan orang yang aku sayangi.
“Tama, Janis sakit. Ayah, Janis…..”
Bunda, melirikku, dan mengecupkan bibirnya di keningku. “Hanya Janis yang Bunda punya”.
Aku membuang pagi untuk menyongsong Dhuha. Bunda telah menanti di lorong ruang hatiku yang lain.
“Maafkan aku bunda, tak mengindahkanmu ada”
Kuharap bukan karena tabrakan itu, Tama termakan kanker. Lalu pergi, menyuruhku menghampiri bunda setelah aku kehilangan kakiku juga.
Yellow pages, 22 Februari 2009
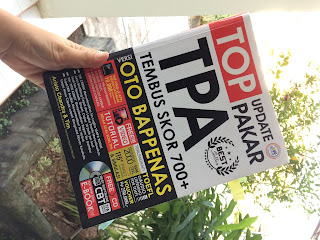


Komentar