Mitos, Data dan Fakta Perempuan Pemimpin
Abstrak
Sebagian besar
masyarakat, menganggap bahwa pemimpin haruslah kaum laki-laki, baik pemimpin dalam
rumah tangga maupun dalam lingkup pekerjaan dan pejabat publik. Tulisan ini
membongkar mitos perempuan pemimpin berdasarkan data dan fakta. Data
membuktikan bahwa perempuan yang duduk sebagai pejabat publik sangat rendah.
Sehingga menimbulkan kebijakan yang tidak responsif gender. Mitos perempuan
pemimpin yang melingkupi perempuan, membuat tidak sedikit terjebak terlalu
dalam pada dunia patriarki.
Marginalisasi membuat perempuan menjadi other dalam kultur yang diciptakan
laki-laki (Beauvoir,
2003:322)
Pendahuluan
Makna yang benar tentang kesetaraan gender belumlah dipahami
oleh sebagian masyarakat kita. Istilah tersebut bahkan lebih sering dilontarkan
sebagai bahan candaan yang maknanya
justru jauh dari semangat kesetaraan gender. Sebagian besar masyarakat menganggap kesetaraan
gender hanya sebatas persoalan
pembagian pekerjaan antara perempuan dan laki-laki, siapa yang melakukan pekerjaan
berat dan pekerjaan ringan,
atau
siapa yang memimpin dan yang dipimpin, yang mengemban tanggung jawab atau yang menjadi tanggung jawab.
Bicara kepemimpinan berarti kita
akan bicara mengenai kekuasaan, jabatan dan kaitan dengan pengambil kebijakan.
Konteks kepemimpinan di tingkat pemerintahan akan sangat berbeda dengan
kepemimpinan di komunitas
paling bawah, yaitu keluarga. Pimpinan di
tingkat
pemerintahan sangat menentukan kebijakan publik yang bukan hanya akan dinikmati
oleh segelintir orang melainkan pula sebagian besar masyarakat.
Kebijakan menjadi poros penting
bagi sendi kehidupan masyarakat. Pada kenyataannya kebijakan yang ada dirasakan
masih belum mengena kebutuhan langsung masyarakat, terutama perempuan dan anak.
Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), biaya kesehatan yang semakin tinggi,
minimnya akses air
bersih, tingginya tingkat pengangguran, rentannya hukum yang melindungi
perempuan korban kekerasan merupakan sebagian kecil permasalahan yang
menjadikan perempuan dan anak sebagai korban.
Berdasarkan data SDKI[1]
terakhir tahun 2007, angka kematian ibu (AKI)
Indonesia sebesar 228 per
100.000 kelahiran hidup, yang berarti bahwa ada 228 ibu meninggal setiap
100.000 kelahiran. Angka tersebut merupakan angka tertinggi di Asia. Selain itu
data menunjukkan kurang dari 40% jumlah penduduk kota di Indonesia yang
memiliki akses terhadap air minum PDAM dan sekitar 6 juta masyarakat miskin
Indonesia membeli air bersih dari penjual keliling dengan melebihi harga air
PDAM (Pokja AMPL)[2].
Walaupun kuota perempuan yang
menduduki jabatan publik telah ada sejak kemerdekaan Indonesia, baik di level
legislatif, eksekutif maupun
yudikatif, namun kenyataannya hingga saat ini jumlah perempuan pejabat publik
masih minim sekali. Hal inilah yang membuat perjuangan berbagai elemen
perempuan menuntut kesetaraan di
kancah
perpolitikan. Berbagai kalangan melihat bahwa perjuangan kebijakan affirmative action merupakan simpul
penting kebijakan lainnya bagi kesejahteraan perempuan dan anak. Untuk
memperjuangkan kepentingan yang berpihak pada kaum marginal, khususnya kaum perempuan dan anak.
Kuatnya dominasi laki-laki dalam tatanan sosial saat ini
memaksa perempuan untuk berusaha
lebih keras agar dapat tampil sebagai pemimpin. Meskipun dengan
perjuangan melawan mitos, tradisi dan kepercayaan dirinya, tidak
sedikit juga perempuan
yang berhasil duduk di bangku kepemimpinan. Dengan menelaah data-data yang tersedia kita dapat menelisik
lebih dalam seberapa besar sebenarnya
jumlah perempuan yang berhasil duduk di bangku pejabat publik.
Kenyataan
Perempuan Parlemen
Saat ini, perempuan mulai diperhitungkan
untuk duduk menjadi pejabat publik,
baik
pejabat di lingkungan
daerah maupun nasional, berada di
posisi
legislatif, yudikatif maupun eksekutif.
Fenomena
ini dapat kita lihat dari besarnya jumlah keterwakilan perempuan di legislatif menurut jenis kelamin mulai tahun 1955-2009,
seperti tabel berikut ini.
Tabel 1. Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin 1955-2009
Tahun Pemilu
|
Laki-laki
|
Perempuan
|
Laki-laki + Perempuan
|
|||
Jumlah
|
Persentase
|
Jumlah
|
Persentase
|
Jumlah
|
Persentase
|
|
1955
|
256
|
94,12
|
16
|
5,88
|
272
|
100
|
1971
|
429
|
93,62
|
31
|
6,38
|
460
|
100
|
1977
|
423
|
91,96
|
37
|
8,04
|
460
|
100
|
1982
|
418
|
90,87
|
42
|
9,13
|
460
|
100
|
1987
|
441
|
88,2
|
59
|
11,8
|
500
|
100
|
1992
|
438
|
87,6
|
62
|
12,4
|
500
|
100
|
1997
|
442
|
88,4
|
58
|
11,6
|
500
|
100
|
1999
|
456
|
91,2
|
44
|
8,8
|
500
|
100
|
2004
|
485
|
88,18
|
65
|
11,82
|
550
|
100
|
2009
|
460
|
82,41
|
100
|
17,59
|
560
|
100
|
Sumber : Statistik Indonesia 2010, BPS RI
Jika dilihat dari data tersebut,
keterwakilan perempuan di parlemen
sudah mulai diperhitungkan sejak pemilihan umum tahun 1955. Ketika
membandingkan persentase jumlah perempuan dan laki-laki yang duduk diparlemen,
membuktikan bahwa persentase perempuan yang duduk diparlemen sangat
rendah.
Dilihat dari penduduk, Indonesia saat ini berada
pada jumlah 237.641.326 jiwa, jumlah
perempuan sebanyak 118.010.413 jiwa dan jumlah laki-laki sebanyak 119.630.913
jiwa dengan seks rasio 101,
yang berarti
terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Seks Rasio nasional pada
kelompok umur 0-4 sebesar 106, umur 5-9 sebesar 106, kelompok umur lima tahunan
dari 10 sampai 64 berkisar antara 93 sampai dengan 109, dan umur 65+ sebesar 81
(Hasil Sensus Penduduk 2010).
Jumlah penduduk perempuan yang
sangat besar tersebut, membuat kita bertanya, apakah kepentingan perempuan
telah terwakili dengan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen? Hal ini dapat
dilihat dari grafik garis mengenai persentase keterwakilan perempuan di DPR.
Tabel
2. Persentase Keterwakilan di Parlemen
(tidak dapat ditampilkan) silahkan cek ke www.bps.go.id
Sumber : Statistik Indonesia 2010, Data Diolah
Dari data diatas, kita dapat
melihat bahwa pada tahun 2009, keterwakilan perempuan di DPR mengalami
peningkatan pada pemilihan umum tahun 2009. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya tuntutan
mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif, yang sangat massif
disuarakan oleh kelompok-kelompok perempuan. Perjuangan tersebut berhasil
mendorong lahirnya kebijakan mengenai keterwakilan perempuan
dalam UU Pemilu Tahun 2003 pasal 65 ayat 1, yang menyebutkan bahwa:
Setiap
Parpol peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/kuota untuk setiap daerah pemilihannya dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
Kenaikan kuantitas keterwakilan
perempuan tersebut jika ditilik lagi lebih lanjut, kenaikannya sedikit sekali.
Karena pada 2004 jumlah anggota legislatif sebesar 550 orang, dan pada 2009
mengalami kenaikan 1,82% menjadi 560 orang. Kenaikan sebesar 1,82% ini
merupakan keran peluang kenaikan jumlah perempuan yang duduk di parlemen
sehingga pada 2009 ada kenaikan sebesar 5,77%.
Kita juga melihat bahwa penurunan
secara kuantitas laki-laki di DPR sebesar 4,46% pada rentang tahun 2004-2009
merupakan sebuah kesadaran pentingnya keterwakilan perempuan dilegislatif. Walaupun
sejatinya, hasil pemilu 2004 dan 2009 sangat mengecewakan untuk keterwakilan
perempuan. Senada
yang dijelaskan oleh Fakih (2001),
Dominasi laki-laki dalam struktur
partai politik, semakin memberikan peluang yang besar kepada laki-laki untuk
menciptakan tatanan politik yang bias gender, karena dominasi satu jenis
seringkali melahirkan hegemoni dan
kebijakan yang bias atas jenis yang lainnya.
Begitu pula yang disampaikan oleh Blackburn (dalam
Rusta, Rika Valentina & Nia Gustiarini), feminis dan analis politik dari Monash Universitiy
Australia, yang mengatakan bahwa sejarah perempuan dan politik di Indonesia selalu
diwarnai dengan kejutan. Karena sejak pasca kemerdekaan perempuan Indonesia telah
mencapai tingkatan-tingkatan politik yang jauh lebih maju dibandingkan dengan
negara lain. Sejak tahun 1945 hak perempuan untuk memilih telah diakui, posisi
perempuan dalam politik berlangsung berlangsung secara fluktuatif sehingga
saat-saat terakhir menjelang pemilu 2004.
Lebih lanjut Blackburn mengatakan berubahnya status perempuan tersebut disebabkan karena
proses demokrasi di Indonesia tidak melalui cara-cara bertahap tetapi melalui
lompatan-lompatan. Setiap lompatan demokrasi menghasilkan visi-visi politik
negara yang berbeda, bahkan terkadang sangat dramatis dalam konteks persoalan perempuan. Karenanya, sebelum sistem politik
diperkuat dengan konstitusi dan aturan hukum yang berpihak pada perempuan,
dapat dipastikan pembangunan nasib perempuan yang bersifat berkesinambungan
tidak akan pernah ada.
Walaupun pada 2009 target kuantitas
keterwakilan perempuan belum tercapai,
kenaikan 5,77% keterwakilan perempuan di legislatif adalah tonggak
penting dalam perjuangan keterwakilan perempuan untuk menuju keterwakilan
perempuan 30%. Perjuangan menuju kearah tersebut terus menerus dilakukan dengan
harapan agar perempuan bisa sejajar dengan laki-laki dalam kehidupan publik secara adil, serta menciptakan
kebijakan-kebijakan yang pro keadilan.
Kenyataan Kepemimpinan Perempuan di Eksekutif
Selain di legislatif, secara kuantitas
perempuan masih menjadi kelompok nomor dua menduduki jabatan di tingkat eksekutif. Hal ini dapat
dilihat dari data dibawah ini.
Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan
dan Jenis Kelamin
Jabatan
|
2008
|
2009
|
2010
|
||||||
Lk
|
Pr
|
Jumlah
|
Lk
|
Pr
|
Jumlah
|
Lk
|
Pr
|
Jumlah
|
|
Fungsional Tertentu
|
915354
|
1078525
|
1993879
|
950740
|
1189824
|
2140564
|
927360
|
1172288
|
2099648
|
Fungsional Umum/staf
|
1161897
|
696966
|
1858863
|
1323373
|
827016
|
2150389
|
1363838
|
915585
|
2279423
|
Struktural
|
180157
|
50461
|
230618
|
181156
|
52096
|
233252
|
169085
|
49944
|
219029
|
Eselon V
|
9847
|
2938
|
12785
|
9241
|
3054
|
12295
|
8972
|
3045
|
12017
|
Eselon IV
|
130607
|
41365
|
171972
|
130233
|
42261
|
172494
|
122074
|
40483
|
162557
|
Eselon III
|
32501
|
5593
|
38094
|
34323
|
6174
|
40497
|
31581
|
5882
|
37463
|
Eselon II
|
6695
|
508
|
7203
|
6783
|
556
|
7339
|
5965
|
487
|
6452
|
Eselon I
|
507
|
57
|
564
|
576
|
51
|
627
|
493
|
47
|
540
|
Sumber : Statistik Indonesia 2010, BPS RI
Dari
data diatas, kita dapat melihat bahwa rentang 2009-2011 perempuan yang
menduduki jabatan publik mengalami peningkatan jumlah. Hal ini pula sebanding
dengan peningkatan jumlah laki-laki yang menduduki jabatan di lingkungan pemerintahan.
Peningkatan jumlah perempuan yang menduduki jabatan dapat dilihat pada posisi
jabatan fungsional tertentu. Pada 2008 hampir 54,09% perempuan menduduki
jabatan fungsional tertentu begitu pula pada 2009 hampir 55,59 % dan 2010, 55,83%.
Namun demikian posisi keterlibatan
perempuan dalam pengambil keputusan penting belum signifikan. Ini terlihat dari
penempatan perempuan yang masih mendominasi posisi jabatan fungsional tertentu.
Tabel 4. Persentase Jabatan
Fungsional Tertentu
Sumber : Statistik Indonesia 2010, data diolah
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16
tahun 1994, ayat 1 :
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
dalam Peraturan Pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri
Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri
Jabatan Fungsional, merupakan jabatan teknis yang
tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya
sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi. Jabatan
fungsional tertentu merupakan jabatan fungsional yang sering dikonotasikan
sebagai pekerjaan perempuan. Seperti perawat, bidan, guru, terapis, widyaiswara,
dosen, penyuluh kesehatan dan sebagainya. Walaupun juga jumlah laki-laki yang
menduduki posisi ini tidak sedikit jumlahnya.
Pada level pengambil kebijakan,
perempuan yang duduk di tataran
eselon masih sedikit sekali. Tahun 2008, perempuan hanya menduduki sekitar
10,11 % posisi eselon I, dan sekitar 8,85 % pada 2009 serta 8,7% di 2010. Pada
eselon II, jumlah perempuan sekitar 7,05 % pada 2008, 7,58 % pada 2009 dan
7,75% pada 2010.
Perempuan
paling banyak menduduki posisi eselon V dan eselon IV. Kedua posisi eselon ini,
ditempati perempuan masing-masing pada 2008 sebesar 22,98 % dieselon V dan
24,05 % dieselon IV. Tahun 2009, perempuan menduduki posisi sebesar 24,84 % dieselon V dan 24,50 % dieselon IV. Sedangkan
pada 2010 perempuan menduduki posisi sebesar 25,34% dieselon V dan 24,90%
dieselon VI.
(tidak dapat ditampilkan) silahkan cek ke www.bps.go.id
Tabel
5. Persentase Pejabat Eselon tahun 2009
Sumber : Statistik Indonesia 2010, data diolah
Sangat sedikitnya keterlibatan perempuan
dalam pengambilan
keputusan dan proses penyusunan kebijakan cukup memprihantinkan kita. Stagnasi
jumlah perempuan dalam
proses
kebijakan juga membuat stagnasi kebijakan yang berpihak pada perempuan. Menurut Carrigan, Connel, dan Lee (dalam
Patria, 1999), kebanyakan
laki-laki memperoleh keuntungan dari subordinasi kaum perempuan, dan
maskulinitas hegemonik terkait dengan pelembagaan dominasi laki-laki atas
perempuan.
Dalam penyusunan
kebijakan pemerintah di tingkat
pusat maupun daerah, misalnya sampai saat ini masih belum ada prioritas pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat dan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, kebutuhan dasar masyarakat
seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, akses terhadap air bersih, perbaikan
sarana fasilitas umum dan sosial lainnya, masih belum terpenuhi.
Pengabaian negara terhadap kewajiban untuk memenuhi kebutuhan
dasar tersebut mempunyai dampak paling
besar terhadap
perempuan dan anak, karena
akan berakibat terhadap anggaran rumah tangga, kesehatan fisik dan reproduksi,
timbulnya bebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kecilnya
akses pendidikan pada perempuan dan anak-anak. Jadi perempuan mengalami
penderitaan berlipat ganda dan lebih rentan terhadap pelanggaran HAM ketika
kebutuhan dasarnya diabaikan (Rosidawati, 2004).
Mitos Perempuan Pejabat Publik
Tidak sedikit peranan kepemimpinan perempuan
dipertanyakan oleh publik. Kebijakan apa yang sudah
dihasilkan? Apa peranan signifikan dalam kebijakan yang sudah dilakukan? Apakah
pemimpin perempuan sudah
benar-benar memperjuangkan kaum perempuan? Serta sederet pertanyaan
lain yang masih menjejali kepala kita mengenai peranan perempuan di
kepemimpinan.
Sebelum kita menilik mitos
perempuan bekerja dan perempuan
pemimpin,
kita akan menilik jumlah penduduk usia kerja (15
tahun ke atas) sebesar 169,0 juta jiwa. Terdiri dari 84,3 juta orang laki-laki
dan 84,7 juta orang perempuan. Dari jumlah tersebut, jumlah angkatan kerja,
yakni penduduk 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi yaitu mereka yang
bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha sebesar 107,7 juta jiwa,
yang terdiri dari 68,2 juta orang laki-laki dan 39,5 juta orang perempuan.
Dilihat
berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah angkatan kerja yang tinggal di
perkotaan sebesar 50,7 juta orang dan yang tinggal di perdesaan sebesar 57,0
juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja
sebanyak 104,9 juta jiwa dan yang mencari kerja sebesar 2,8 juta jiwa (Hasil
Sensus Penduduk 2010).
Data data diatas kita dapat melihat
bahwa ada 36,68% perempuan yang aktif secara ekonomi. Perempuan yang aktif
secara ekonomi tentu saja mengalami beban ganda dalam kehidupannya. Tentu tidak
usah kita bahas lagi, tidak sedikit perempuan harus terbebani dengan beban
ganda (double burdon). Disatu sisi
harus mencari nafkah, dan disisi lain memiliki tanggungjawab yang besar dalam
peranannya menjadi ibu rumah tangga. Beban kerja tersebut menjadi dua kali
lipat bagi kaum perempuan yang juga bekerja di luar rumah dan harus bertanggung
jawab untuk keseluruhan pekerjaan domestik (Fakih, 2001).
Suka tidak suka, ketika menikah
perempuan langsung mendapat peran menjadi ibu rumah tangga. Potret kehidupan perempuan di daratan patriarki memang begitu adanya. Pelekatan status dan
tanggung jawab yang diberikan oleh negara
sudah ajeg (konstan), karena diatur jelas dalam undang-undang. Sehingga mau
tidak mau, perempuan selalu berada pada posisi yang sangat sulit, antara pekerjaannya atau
keluarganya.
Dalam istilah Hegemoni yang
ditemukan oleh Gramsci, patriarki dan segala atribut maskulinitasnya terus saja
dipersuasikan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan budaya termasuk
juga media massa (Connel dalam Patria).
Pengaturan
oleh Negara juga dituangkan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 ayat 3 yang menegaskan
bahwa :
‘suami
adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga’
Pasal ini secara jelas dan tegas
mendukung pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang dalam
masyarakat. Hal ini semakin dipertegas dalam pasal 34 UUPerkawinan No. 1 Tahun
1974, bahwa :
“suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga
sebaik-baiknya”
Peraturan ini dengan sangat jelas membatasi peran perempuan diranah
publik dan menempatkan perempuan sebagai sub-ordinat. Hal ini dapat menyebabkan
ketimpangan gender yang berujung pada ketidakadilan gender seperti kekerasan
terhadap perempuan. Peraturan tersebut secara tidak sadar telah mengakibatkan semakin tingginya praktek diskriminatif
yang merugikan salah satu golongan tertentu.
Pada kenyataannya tidak sedikit
pula perempuan yang memilih
bekerja dan mengurus pekerjaan rumah tangga dengan bersamaan. Atau dekade ini
banyak yang menyebutnya sebagai ‘wanita karir’. Berarti
perempuan yang ambisius mengejar karir di
lingkungan
pekerjaan dan sekaligus mampu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Bukankah
begitu mitosnya? Asumsi di masyarakat ‘wanita karir’ merupakan
perempuan hebat yang memiliki kemampuan bersaing di dunia kerja tanpa meninggalkan
embel-embel status ibu rumah tangga.
Bahkan perempuan akan dilabelkan
sebagai perempuan jika urusan kerumahtanggaan beres walaupun perempuan juga
mencari nafkah. Jika tidak label ‘perempuan tidak becus’, akan melekat di dalam dirinya. Termasuk sering
dipersalahkannya perempuan secara sepihak atas persoalan dalam mengurus rumah tangga. Konsep
stretotip
perempuan seperti inilah yang menciptakan label bahwa
perempuan merupakan individu yang reproduktif, dan jika perempuan masuk ke ranah produktif berarti
perempuan telah melangkahi kodratnya. Laki-laki menggunakan
kekuasaan dan kekuatannya atas diri perempuan untuk menunjukkan fungsi dan peranannya
yang lebih kuat dari perempuan.
Tidak sedikit pula perempuan yang
bekerja di ranah publik harus membawa urusan kerumahtanggaan ke tempat bekerja.
Misalnya membawa anak ke tempat kerja, datang terlambat karena harus memasak
dan mengantar anak ke sekolah, serta sederet pekerjaan rumah yang dibawa dalam
dunia kerja. Beban, tanggung jawab
akan pendidikan dan kehidupan anak sering
kali
dibebankan kepada perempuan, sehingga ketika tiba ditempat bekerja, perempuan
tidak dapat bekerja dengan baik, yang akhirnya perempuan merasa nyaman berada
di posisi yang tidak strategis. Tanggung jawab yang lebih berat, rutinitas
dan mobilitas jabatan publik membuat banyak perempuan akhirnya memilih tidak
ingin bersaing dengan kaum laki-laki dalam perebutan jabatan publik.
Selain, juga kondisi budaya yang
juga mengkondisikan laki-laki sebagai pemimpin tidak lepas dari keengganan
perempuan menduduki posisi pejabat publik. Senada yang disampaikan Widarsono dalam
Wiji Rahayu (2009):
“Sistem nilai
dan budaya berkontribusi terhadap langgengnya patriarki yang telah melekat dari
generasi ke generasi, yang menyubordinatkan perempuan di bawah superioritas
laki-laki. Perempuan masih diposisikan sebagai kelompok lemah dan perlu
diajari, dibimbing, dan diamankan. Semua itu menjadi pembenaran perempuan tidak
bisa berperan di ruang publik, diharuskan tinggal di rumah demi keamanannya,
dan berkonsentrasi di wilayah domestik”
Banyak hal yang membuat
keterlibatan perempuan dijabatan strategis belum diprioritaskan. Suka tidak suka harus diakui bahwa
dilingkungan kita, laki-laki pasti dianggap pemimpin dan ditasbihkan layak
menjadi pemimpin. Kelayakan tersebut biasanya ditunggangi oleh kondisi budaya patriarki
yang secara masif memposisikan laki-laki sebagai kaum kelas satu. Mitos-mitos
seperti seringkali membuat perempuan belum memiliki tempat yang sejajar dalam
tatanan strategis. Sesuai dengan pendapat Fakih (2001) :
Marjinalisasi terhadap
kaum perempuan terjadi
secara multidimensional yang
disebabkan oleh banyak
hal, bisa berupa
kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan, tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan
Belum lagi pertanyaan
apakah peranan signifikan perempuan dalam kancah jabatan strategis dijawab
namun secara kasat mata kita dapat melihat bahwa belenggu mitos yang selama ini
menerjang kaum perempuan membuat sebenarnya kita tau bahwa permasalahan perempuan
menjadi pemimpin memang sedari awal sangat tipis peluangnya. Label
perempuan hanya bekerja dalam ranah domestik sudah dipatenkan mejadi label yang
tidak dapat diubah. Sedangkan peran kepemimpinan, penguasaan dan superioritas
berada dalam gengaman laki-laki (Foucoult dalam Agger, 2008)
Mitos minimnya rasionalitas dalam
diri perempuan dan lebih sering menggunakan perasaan juga melingkupi alasan
mengapa perempuan belum layak menjadi
pemimpin, sehingga pilihan jatuhnya puncak pimpinan kepada laki-laki lebih
sering dikatakan tepat dalam kenyatannya.
Pemberian
julukan, cap, etiket, merek yang diberikan kepada perempuan bahwa perempuan
adalah makhluk domestik yang reproduktif merupakan sebuah perlakuan yang
diskriminatif. Penguatan pola ini diperkuat dengan tanggapan komunitas
masyarakat, sehingga memperkuat citra diri perempuan sebagai individu
reproduktif (Chambliss dalam Sunarto, 2004)
Sifat feminin yang dilekatkan pada
perempuan membuat banyak pekerjaan yang direpresentasikan sebagai pekerjaan
perempuan. Guru, perawat, bidan dan sebagainya yang terkait dalam pekerjaan
fungsional tertentu menjadi pekerjaan yang dikonotasikan pada perempuan, dikarenakan
sifat keibuan, perasaan dan ketelitian yang selalu dilekatkan pada perempuan.
Refleksi hal ini, membuat kerentanan peluang perempuan menduduki jabatan
strategis menjadi sangat minim. Senada yang diungkapkan,
Jenis
pekerjaan wanita sangat ditentukan oleh seks, sedangkan laki-laki tidak.
Pekerjaan wanita selalu dihubungkan dengan sektor domestik, jika ia bekerja
maka tidak jauh dari kepanjangan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti:
Bidan, perawat, guru dan sekretaris yang lebih banyak memerlukan keahlian
manual saja (Amin, 1992).
Kematangan perempuan yang menduduki
jabatan juga acap kali menjadi cibiran. Kebijakan yang diambil seringkali dicap
hanya menggunakan perasaan dan emosionalitas daripada rasionalitas. Hal
tersebut membuat perempuan menjadi tidak nyaman untuk mengambil kebijakan yang
pada akhirnya membuat perempuan merasa minder dan akhirnya mundur dari kancah
persaingan.
Kesimpulan
Dominasi laki-laki dalam
pengambilan kebijakan masih tinggi sekali. Perempuan yang duduk diparlemen pada
2004 sebesar 11,82% dan 2009 sebesar 17,59%, sedangkan rentang 2008-2011 sedikit
sekali perempuan yang menduduki bangku pengambil kebijakan ditingkat eselon V
hingga I. Rata-rata jumlah perempuan yang menduduki posisi tersebut hanya
16,09%. Perjuangan untuk mencapai komposisi yang ideal tampaknya membuat kaum
perempuan masih harus bekerja ekstra keras. Terlebih lagi beratnya mitos yang
dilekatkan pada perempuan pemimpin. Kita harus bahu-membahu menciptakan iklim
yang sehat supaya perempuan dapat memperoleh kesempatan yang sama dengan
laki-laki. Dimulai dari dari kita sendiri, keluarga dan menciptakan
pemimpin-pemimpin perempuan yang tangguh, sensitif dan berorientasi pada
kemajuan kaum perempuan dan anak.
Daftar Pustaka
Agger,
Ben. (2008). Teori Sosial Kritis; Kritik, Penerapan dan Implikasinya,
Kreasi Wacana, Yogyakarta
Beauvoir,
de Simone. (2003), Second Sex : Fakta dan Mitos, Pustaka Promethea,
Surabaya
BPS
RI. (2010), Statistik Indonesia 2010,
Jakarta
Faqih, Mansour. (2001), Analisis Gender dan Transformasi Sosial,
Pustaka Pelajar Yogyakarta
Amin, M Mansyur. (1992) Wanita dalam Percakapan Antara Agama
Aktualisasi Dalam Pembangunan, LKPSM NU DIY, Yogyakarta
Patria,
Nezar. (1999), Antonio Gramsci Negara dan
Hagemoni, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Pokja AMPL. Data Air Minum. Melalui
http://digilib-ampl.net/detail/list.php?tp=fakta&ktg=airminum,
dilihat pada 21 Oktober 2012
Rusta, Andri & Rika Valentina,
Tengku & Nia Gustriani, Nicky. Affirmative Action untuk Demokrasi yang Berkeadilan Gender Pada Pemilu 2009.
Melalui
http://repository.unand.ac.id/584/. Dilihat pada 25
September 2012
Rosidawati, Imas. Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan
Rakyat Kesiapan Partai Politik dan Perempuan Indonesia di Arena Politik Praktis.
Melalui http://www.uninus.ac.id/data/data_ilmiah/Quota%20Perempuan%20di%20DPR.pdf.
Dilihat pada 15 September 2012
Sunanto,
Kamanto. (2004), Pengantar Sosiologi, Lembaga penerbit FE UI, Jakarta
Wiji
Rahayu, Angger. (2009), Film Perempuan
Berkalung Sorban dan Representasi Ideologi Patriarki (Sebuah Analisis Wacana
Kritis dan Semiotika), Skripsi, Universitas Bengkulu
Penulis :
Angger Wiji Rahayu, aparatur di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan.
Seorang blogger di www.anggerwijirahayu.com, aktif dalam kelompok penulis muda Bengkulu, relawan di PKBI Bengkulu dan Cahaya Perempuan WCC Bengkulu.
[1] Survei
Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI). Survei ini dilakukan setiap lima tahun
sekali oleh Badan Pusat Statistik.
[2] Kelompok
Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) yang
terdiri dari berbagai Kementerian dan Badan terkait sertaunsur non pemerintah
dan dunia usaha yang konsen terhadap isu penyehatan lingkungan dan penyediaan
air minum
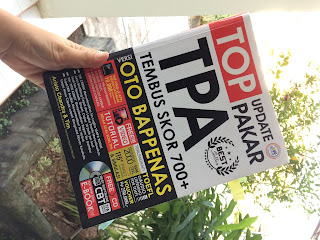


Komentar