Representasi Pemberitaan Perempuan dalam Media Massa
Bukan sebuah rahasia lagi, jika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, berita tersebut menjadi bulan-bulanan media. Media kita masih menjadi media yang sangat menyukai bentuk-bentuk berita yang mengorek-ngorek pribadi individu. Kasus-kasus pribadi menjadi sangat penting dalam headline media, bahkan kasus-kasus tersebut seringkali dijadikan alasan politis untuk kepentingan tertentu. Perempuan korban kekerasan seringkali menjadi objek kekerasan kedua kalinya dalam media untuk melanggengkan bukan hanya kepentingan politis tertentu, namun juga kepentingan media terhadap sebuah pemberitaan.
Walaupun seringkali media mencoba menghormati perempuan korban kekerasan terhadap perempuan, misalnya dengan menyembunyikan identitas korban dan menyampaikan deskripsi kronologis kasus dengan singkat, namun cukup banyak media lain justru melakukan kekerasan dengan pengobjekan perempuan korban kekerasan. Media seringkali bersikap tidak adil kepada korban, bahkan yang lebih naifnya lagi, media bersimpati kepada pelaku. Media mengobjekkan korban sebagai perempuan yang juga awalnya merupakan pelaku terjadinya tindak kekerasan. Seperti yang diungkapkan oleh Piliang dalam Sorbur,
“Kekerasan terhadap perempuan—dengan mengacu pada pengertiannya yang paling luas—pada kenyataannya tidak hanya berlangsung pada tingkat ‘realitas’ (berupa pemukulan, perkosaan atau pelecehan) akan tetapi juga pada tingkat ‘representasi’ dari realitas tersebut di dalam berbagai media representasi.”
Artinya, bagaimana bentuk dan cara sebuah ‘realitas kekerasan’ direpresentasikan di dalam berbagai media representasi telah merupakan sebuah bentuk ‘kekerasan’ itu sendiri. Sehingga sikap tidak empatis pada korban, dan bias gender yang berpihak pada pelaku pada berita merupakan sebuah representasi dari kekerasan terhadap perempuan itu sendiri dalam media. Apalagi jika perempuan korban kekerasan diberi stigma sebagai “bukan perempuan baik-baik”. Sehingga secara tidak sadar, memaksa masyarakat memberikan arti bahwa kekerasan terhadap perempuan diawali oleh perempuan itu sendiri sebagai penyebab terjadinya kekerasan. Sungguh suatu pemaksaan yang tidak adil, yang melanggengkan budaya patriarki itu sendiri dalam masyarakat.
Contoh yang sangat konkret adalah terlihat dari pemilahan bahasa yang digunakan media untuk menggambarkan suatu kejadian perkosaaan. Dengan menggunakan ”bahasa banci” yang memaksa masyarakat meraba-raba dan menebak-nebak makna yang terkandung. Misalnya saja contoh judul berita perkosaan di media cetak ”Remaja ABG Digarap Sepulang Sekolah” atau ”Digauli ayah Tiri selama 1 Tahun”. Kedua contoh judul diatas merupakan sebuah bentuk representasi kekerasan terhadap perempuan dalam media massa. Bagaimana tidak, perempuan diposisikan sebagai kaum yang lemah yang hanya ingin diposisikan sebagai ”korban” yang tak berdaya. Penulisan judul saja sudah membuat asumsi dalam benak masyarakat bahwa perempuan merupakan mahluk yang bisa diperlakukan semena-mena.
Ini belum lagi termasuk kedalam isi yang juga sarat akan kekerasan terhadap perempuan pada tingkat representasi. Seringkali deskripsi korban dijadikan senjata secara sengaja untuk menggambarkan bahwa perempuan juga merupakan pelaku. Contohnya saja, ”Gadis (Bunga bukan nama sebenarnya, 16 tahun), bertubuh sintal dan kulit putih digarap pada saat pulang sekolah disebuah gubuk”. Secara naluriah, jika kita membaca tulisan ini, maka kita akan berasumsi bahwa perempuan tersebut memancing laki-laki untuk melakukan tindakan kekerasan. Bukankah itu suatu bentuk kekerasan secara psikologi yang kedua kalinya didapatkan oleh perempuan? Starting pointnya yang perlu digaris bawahi adalah ”Perempuan mana yang ingin terjadi kekerasan dalam hidupnya?”
Media sebagai Agen Konstruksi Realitas
Pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Isi media adalah hasil dari konstruksi realitas yang dipilih para pekerja media untuk ditampilkan kepada khalayak. Konstruksi realitas pada media merupakan hasil peristiwa-peristiwa tertentu yang dipilih berdasarkan kepentingan-kepentingan. Menurut Bauer dan Bauer dalam Barker (2000:278), menyatakan bahwa media yang berkembang dengan baik mengemban pengaruh yang cukup untuk membentuk opini dan keyakinan, mengubah kebiasaan hidup. Secara aktif media juga membentuk perilaku yang kurang lebih sesuai dengan keinginan orang-orang yang dapat mengendalikan media dan isinya. Semua teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu (Eriyanto, 2001:13).
Media massa menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Dengan demikian seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan (constructed reality) dalam bentuk wacana yang bermakna. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak (Hamad, 2004:11-12). Namun, ada sebuah konsep filosofis yang mengatakan bahwa yang kita lihat bukanlah realitas, melainkan representasi (sense datum) atau tanda (sign) dari realitas yang sesungguhnya, yang tidak dapat kita tangkap. Yang dapat ditangkap hanyalah tampilan (appearance) dari realitas dibaliknya (Straaten dalam Sorbur, 2006:930).
Dalam konteks media-khususnya pemberitaan mengenai perempuan di dalamnya-representasi perempuan didasarkan atas sebuah ideologi besar. Menurut Piliang, ada banyak prinsip bagaimana ideologi beroperasi dalam produksi makna-termasuk makna dalam media. Di antara prinsip tersebut adalah apa yang disebut sebagai prinsip ‘oposisi biner’ (binary opposition), yaitu semacam prinsip polarisasi segala sesuatu (tanda, kode, makna, stereotip, identitas) yang di dalamnya terjadi proses generasilasi dan reduksionisme, sedemikian rupa sehingga segala sesuatu dikategorikan ke dalam dua kelompok yang ekstrim, saling bertentangan dan kontradiktif.
Dalam media mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan konsep-konsep oposisi biner tersebut, terpolarisasi dari ideologi patriarki secara garis besar. Ideologi patriaki membagi prinsip oposisi biner dalam konsep maskulinitas dan feminitas yang terkonstruksi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan diposisikan secara budaya sebagai makhluk yang lemah dan tak berdaya. Sedangkan laki-laki diposisikan sebagai mahluk yang kuat dan mendominasi. Bahkan perumpamaan ini hanya sedikit sekali ungkapan mengenai konsep maskulinitas dan feminitas. Pembagian prinsip-prinsip dasar sifat ini terkonstruksi dalam masyrakat kita yang patriarki, sehingga adanya penerimaan secara mutlak yang tidak adil dalam masyarakat. Penegasan ini didukung oleh media yang dianggap sebagai agen informasi.
Lebih lanjut menurut Piliang, di dalam media-termasuk media pers-ideologi beroperasi pada tingkat bahasa, baik ‘bahasa tulisan’ maupun ‘bahasa visual’. Ideologi pada tingkat bahasa atau linguistik melibatkan yang pertama, pilihan (choices) kata-kata, kosa-kata, sintaks, gramar, cara pengungkapan, pada tingkat paradigmatik (perbendaharaan bahasa), dan yang kedua, tingkat seleksi (selection) yaitu penentuan kata atau bahasa berdasarkan pada berbagai pertimbangan ideologis.
Jika begitu, dominannya ideologi patriarki mempengaruhi kehidupan masyarakat menjadikan polarisasi maskulin dan feminin menjadi suatu bentuk yang konkret dan kodrat, bukan hanya ideologi saja. Kodrat baru yang diterima oleh masyarakat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penerimaan apa yang disampaikan oleh media. Bahwa maskulin dan feminin merupakan kodrat bukan hasil konstruksi sosial. Dan itu direduksi secara massal oleh masyarakat. Sungguh naif, jika kita tak mampu menjabarkan yang mana kodrat dan yang mana konstruksi realitas, padahal kita hidup di era yang penuh dengan informasi.
Daftar pustaka :
Barker, Chris. (2000), Cultural Studies, Bentang,
Hamid, Hasan Lubis. (1993), Analisis Wacana Pragmatik, Angkasa,
Sobur, Alex. (2006), Semiotika Komunikasi, Remaja Rosdakarya,
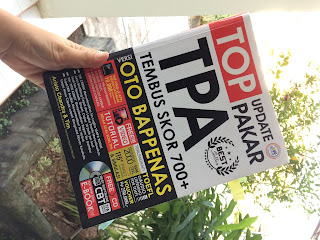


Komentar